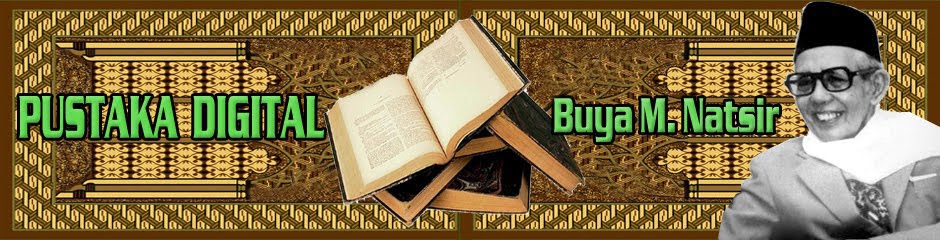Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan tersirat.
”Orang yang pakai jilbab itu adalah sebaik-baiknya muslimah. Tapi yang tidak pakai jilbab jangan dibilang enggak baik.”
Pernyataan itu datang dari Mohammad Natsir. Pejuang Islam yang gigih itu menyampaikan pandangannya tentang jilbab kepada sejumlah pelajar yang datang ke kantor Dewan Dakwah pada awal 1980-an. Ketika itu pemerintah melarang murid mengenakan jilbab di sekolah. Sejumlah pelajar menentang aturan itu dan berujung ke pengadilan. Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretariat Negara, yang dijuluki Natsir Muda, menjadi pembelanya.
”Mereka berkeras soal jilbab. Kalau tidak berjilbab dianggap tidak baik,” Yusril berkisah kepada Tempo. Natsir pun menegur para pelajar yang dinilainya cenderung meremehkan orang Islam tak berjilbab. ”Saya tidak melihat manusia dari jilbab,” kata Natsir seperti dituturkan Yusril.
Natsir, sang pejuang. Dia dikenal sebagai pendidik yang keras, tapi moderat dan demokratis dalam menerapkan ajaran Islam. Dia tidak mewajibkan jilbab kepada istri dan anak-anaknya. Nurnahar, istri Natsir, seperti laiknya orang Melayu dan umumnya warga Masyumi. Sehari-hari dia tampil berkebaya panjang atau baju kurung tanpa kerudung. Ketika menghadiri acara keluarga atau melayat, Natsir baru mengingatkan Nurnahar agar berkerudung.
Mengingatkan pun, menurut Sitti Muchliesah atau Lies, putri sulung Natsir, tidak dalam bentuk perintah.
Dalam berpakaian, Natsir hanya mengharuskan anak-anaknya berbusana santun. Itu artinya, tidak bercelana pendek dan berbaju you can see alias baju tak berlengan. Satu kali, Lies mengenakan blus pendek tanpa lengan.
Masih soal pakaian, ada kenangan yang berkesan bagi Anies, putri Lies, cucu pertama Natsir. Satu kali, sepulang kuliah, Anies mampir ke rumah kakeknya di Jalan Cokroaminoto. Dia datang mengenakan rok mini yang sedang jadi mode. Tatkala hendak pulang, Natsir memberinya uang sambil berkata, ”Ini untuk beli celana panjang.” Teguran halus.
Sekalipun keempat putrinya telah menunaikan ibadah haji, Natsir tak memaksa mereka mengenakan jilbab. ”Menurut Aba, berjilbab itu harus dari diri kita,” tutur Lies, yang kini berusia 72 tahun.
Natsir juga tidak melarang keluarganya bergaul dengan non-muslim. Bergaul dengan teman-teman lelaki pun diizinkan sang ayah. ”Kami boleh nonton bioskop asal rame-rame, paling telat pulang pukul 10 malam.”
Dalam salah satu
Sikap demokratis Natsir tampak jelas di meja makan. Dia mengizinkan anak-anaknya berdebat apa saja, meskipun kadang Ummie tidak berkenan karena perdebatan mengganggu suasana makan. ”
Pada masa penjajahan Jepang, sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikan Natsir di Bandung ditutup. Dia lalu membentuk madrasah di rumah adik iparnya di
Bagi Natsir, pesantren atau madrasah bukanlah satu-satunya sistem pendidikan yang bisa menghasilkan orang beriman. Pesantren, menurut Natsir, dapat menelurkan orang berakhlak tetapi buta terhadap perkembangan dunia. Padahal, Islam mendorong umat mencapai kemajuan lahir batin, dunia dan akhirat.
Itu sebabnya dia tidak melarang anak-anaknya aktif berkesenian. Lies diizinkan mengikuti pementasan sandiwara di sekolahnya, SMA 1 Boedi Oetomo. Entah kenapa, ketika sandiwara yang disutradarai Koentjoroningrat itu hendak dipertunjukkan untuk umum di Gedung Kesenian
Di mata anak-anaknya, ia selalu menyampaikan pesan secara tersirat. Dia juga orang yang berpikiran jauh ke depan. Sewaktu tinggal di
Natsir, sang pendidik. Dia tak begitu setuju anak-anaknya bekerja di perusahaan milik negara maupun swasta. Natsir lebih suka anak-anaknya menggeluti dunia pendidikan. Toh, dia tak bisa berbuat banyak ketika Hasnah Faizah, putri ketiganya, berganti haluan dari asisten dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas
Di kemudian hari, keluarga paham mengapa Natsir tak begitu suka anak-anaknya bekerja di perusahaan. ”
Sebagai Vice President World Muslim Congress, yang bermarkas di
Selama menjadi pejabat pemerintah, hampir tak ada kemewahan yang dinikmati anak dan istrinya. Rumah pribadi pun baru dimiliki setelah Natsir bebas dari penjara pada 1967, jauh setelah penggemar biola ini tak lagi berpangkat.
Suatu ketika Fauzi, anak bungsu Natsir, meminta dibelikan sepeda motor kepada
Natsir juga membebaskan putra-putrinya memilih jurusan sekolah dan tempat bekerja. Lies, misalnya, memasuki Jurusan Sastra Inggris Universitas
Natsir memutuskan, Lies dan adiknya, Asma Faridah, sebaiknya konsentrasi saja pada urusan rumah tangga. Tapi adik-adik Lies, yakni Aisyah, Hasnah, dan si bungsu Ahmad Fauzi Natsir, menyelesaikan kuliah.
Selain Fauzi, ada lagi satu anak lelaki Natsir, yakni Abu Hanifah, yang meninggal pada usia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang. ”
Tangisan itu berulang ketika Natsir kehilangan sang istri. Nurnahar meninggal pada Juli 1991, dalam usia 86.
Dalam salah satu suratnya, Natsir menulis: Ummie sadar jalan hidup yang
Sebelum jenazah sang istri diberangkatkan ke makam, Natsir sendiri yang menyampaikan pidato pelepasan. Dua tahun kemudian, Natsir dimakamkan di samping makam Nurnahar. Kata Lies, ”Seperti keinginan
"Aba, cahaya keluarga", Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008