Natsir gencar mengkritik kaum nasionalis yang merendahkan Islam di majalah Pembela Islam. Tapi dia juga membela Soekarno.
Mohammad Natsir pernah terpesona pada ajaran nasionalisme yang dikumandangkan Partai Nasional Indonesia. Dia pun cukup rajin mendatangi rapat Partai yang senantiasa menggelorakan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu. Bahkan Natsir pernah menghadiri orasi Soekarno, yang ketika itu terkenal sebagai Pemimpin Besar Partai Nasional Indonesia, di Bandung.
Tapi Natsir terperanjat ketika dia mendengar ejekan terhadap Islam semakin sering muncul di tengah kampanye Partai Nasional Indonesia pada kurun 1920-1930.
Sadarlah Natsir bahwa gerakan kebangsaan yang dipelopori Soekarno dan kawan-kawannya mulai menyemai bibit kebencian dan meremehkan Islam. Padahal, pada saat itu, Partai Nasional Indonesia dan Partai Syarekat Islam
Kondisi politik ketika itu membuat Natsir gelisah. Dia banyak belajar pengetahuan Islam dari A. Hassan, gurunya di
Natsir pun tak tinggal diam. Bersama teman-temannya di majalah Pembela Islam ia mulai mengeluarkan tulisan pedas yang menyerang balik kelompok nasionalis. Majalah bulanan seukuran 12 x 19 sentimeter itu kemudian boleh dikata sebagai media yang isinya sarat dengan berbagai perdebatan dan pemikiran. Mulai dari urusan fikih, pertentangan antaraliran agama dan golongan, sampai ke tema politik dan kebangsaan.
Tak mengherankan, karena begitu ”beratnya” Madjallah Comite ”Pembela Islam”—begitu yang tertulis di halaman depannya—menyuarakan berbagai soal itu, semua penulis menggunakan nama samaran atau inisial. Maklum, penguasa Belanda tidak pernah membiarkan artikel kritis seperti itu bermunculan di tanah jajahan.
Ancaman hukuman delik pers (pers delict) terhadap pengelola dan penulisnya, hingga penghentian penerbitan, selalu membayangi mereka. Menurut guru besar luar biasa Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Dadan Wildan Annas, karena kondisi politik saat itu, dan untuk menyembunyikan diri dari serangan lawan politiknya, penggunaan nama samaran memang hal wajar.
Inisial yang muncul antara lain AH, AL, AM, WS, dan MS. Ahmad Hassan, guru agama Natsir, memakai inisial AH. Sedangkan Natsir sendiri ”menyembunyikan” identitas dengan AM atau A. Moechlis, serta Is. Namun, beberapa penulis dari luar tetap memasang nama asli mereka, seperti Moenawwar Chalil, ulama dari Kendal, Jawa Tengah; dan Abikoesno Tjokrosoejoso, aktivis Partai Syarekat Islam Indonesia.
Sebenarnya, meski menggunakan nama samaran, para pembaca setia Pembela Islam tetap tahu siapa identitas asli penulis, dari
Yang paling seru adalah ”pertempuran” antara Natsir dan kelompok nasionalis, yang disebut sebagai ”Soekarno cs”. Dalam tulisan-tulisannya, Natsir ingin memberikan garis pemisah tegas antara perjuangan kemerdekaan berdasar kebangsaan dan yang berdasar cita-cita Islam. Hal itu makin dikuatkan oleh artikel berjudul ”Kebangsaan Muslimin”. Tulisan ini—yang merupakan reaksi atas penghinaan kaum nasionalis terhadap Islam—sangat menggemparkan, hingga Pembela Islam disebut sebagai ”Pembelah Islam”.
Toh, Natsir jalan terus. Dia bahkan juga mengkritik kaum bid’ah dalam pergerakan kemerdekaan. Menurut dia, kaum bid’ah adalah mereka yang suka mengadakan kegiatan maulud, pesta besar khatam Quran anak-anaknya, dan pesta perkawinan yang berlebihan. Natsir menganggap kaum bid’ah banyak bergabung dalam Partai Syarekat Islam
Kritik Natsir dan kawan-kawan terhadap kaum nasionalis—atau aliran Islam yang tak sejalan dengan pemikiran dan kelompoknya dalam Pembela Islam—memang keras. Namun Natsir tetap maju membela Soekarno, yang selama ini dia kritik, ketika dia diadili pemerintah kolonial Belanda sebelum dibuang ke Ende. Bahkan selama di pembuangan itu, Soekarno paling sering berkorespondensi dengan kelompok Pembela Islam.
Sayang, jejak Pembela Islam kini hanya samar-samar. Kantornya sudah tak bisa dikenali lagi. Dalam salah satu edisi di majalah itu, alamat pengelolanya disebutkan ada di Jalan Lengkong Besar 90,
Satu lagi petunjuk juga tak berbekas.
Bahkan lembaga yang dekat dengan Natsir pun hanya memiliki ”kenang-kenangan” terbatas. Pengurusan Pusat Persatuan Islam (Persis) di
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi. 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
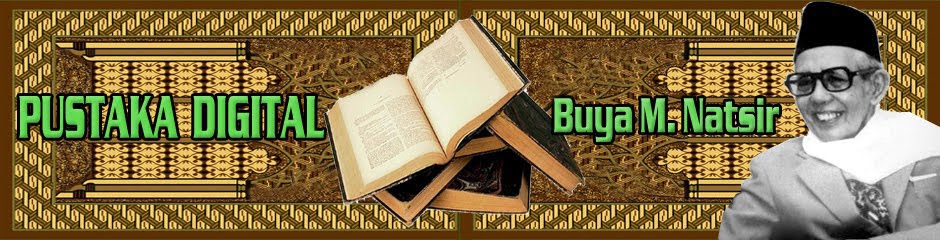
Tidak ada komentar:
Posting Komentar