Di Bandung, sekolah Belanda dan dunia pergerakan membentuk jiwa perlawanan Natsir. Kutu buku yang suka menunggu orkes Homann.
”Engkau dari MULO mana tadinya?”
”Dari MULO
”Eh, pantaslah!”
Pertanyaan itu singkat tapi terasa melecehkan. Hal itu selalu ditanyakan meneer Belanda di sekolah saat bercakap dalam bahasa Belanda dengan Mohammad Natsir. Karena terkesan mengejek, anak muda itu menyimpan kesumat.
Meski sama-sama dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), kemampuan bahasa Belanda Natsir tak sefasih teman-teman dari Jawa. Bahasa Belanda Natsir tak parah-parah amat: menulis dia oke, tapi kalau bercakap-cakap, dia tak lancar. Sekolah Natsir di Padang memang memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar.
Padahal, layaknya sekolah Hindia Belanda di masa itu, hampir semuanya berbahasa pengantar Belanda. Begitupun di Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung. Pada 1927, saat Natsir masuk sekolah ini, AMS, sekolah menengah umum—setingkat sekolah menengah atas sekarang— tergolong sekolah elite dan mahal.
Berdiri pertama kali pada 1919, AMS diperuntukkan bagi lulusan MULO yang ingin melanjutkan sekolah tapi tak mungkin ditampung di Hogere Burger School, yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, Eropa, atau elite pribumi. Sekolah ini hanya ada di Jawa. Dan hanya anak orang berpangkat tinggi yang bisa masuk.
Natsir termasuk yang beruntung. Nilai-nilainya tergolong bagus, sehingga anak pensiunan juru tulis ini mendapat beasiswa Rp 30 masuk AMS Afdeling A-II. Jurusan ini hanya diberikan di AMS
Di Bandung, Natsir tinggal di rumah eteknya, Latifah, di Jalan Cihapit. Jalan itu tak berapa jauh dari sekolahnya di Beliton Straat—sekarang Jalan Belitung. Cukup 15 menit saja berjalan kaki lewat jalan besar.
Tiga bulan pertama di AMS adalah ujian berat bagi Natsir. Sadar selalu diejek karena tak fasih bercakap Belanda, ia melecut diri. Tiap sore, dia belajar bahasa Latin. Selepas magrib, ia melanjutkan pelajaran sekolah. Nyaris tak ada hari libur.
Tiap hari, selepas sekolah, ia membenamkan diri di perpustakaan Gedung Sate untuk melahap buku-buku di bibliotek. Targetnya: satu buku satu minggu. Beberapa bagian dibacanya keras-keras di rumah. Ia juga memberanikan diri terus-menerus bercakap bahasa Belanda.
Di saat kemampuan bercakapnya bertambah, ia ikut lomba deklamasi bahasa Belanda yang digelar sekolah pada akhir tahun. Mengambil satu syair karangan Multatuli berjudul ”De Bandjir”, ia berlatih dengan kawannya, Bachtiar Effendy. Kawannya satu kampung yang duduk di kelas IV-B (khusus eksakta) ini berbahasa Belanda dengan baik. Dia juga dikenal pandai berdeklamasi.
Saat hari lomba tiba, Natsir sengaja memakai baju adat Minang. Sepuluh menit berdeklamasi, tepuk tangan riuh menyambut. Di mukanya tampak Meneer gurunya. Tetap dengan senyum dan tepuk tangan sinis.
Natsir mendapat juara I lomba itu. Hadiahnya buku karangan Westenenk, Waar Mensen Tigger Buren Ziyn (Manusia dan Harimau Hidup Sejiran). Natsir puas karena sudah membayar kesumatnya. ”Setidaknya nama MULO Padang yang selama ini diejek sudah tertebus,” tulis Natsir dalam suratnya kepada anak-anaknya, 50 tahun lampau.
Meski begitu, hati Natsir masih sedikit ”panas” jika melihat gurunya itu. Di kelas V-A (kelas II sekolah menengah atas), ia bertemu lagi dengan si Meneer. Kali ini ia mengajar ilmu bumi ekonomi. Di tengah pelajaran ia suka menyindir pergerakan politik kaum nasionalis. Maklum, siswa AMS pada tahun itu, 1927-1929, suka ikut bicara soal politik. Dan si Meneer tak suka.
Suatu kali, Meneer memberikan pelajaran pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Ia menyuruh muridnya menulis makalah. Butuh dua pekan bagi Natsir untuk menyelesaikan tugas paper-nya itu. Tiap hari ia membenamkan diri di perpustakaan Gedung Sate, mencari literatur tentang pabrik gula itu. Dikumpulkannya jurnal terbitan kaum pergerakan. Juga notula perdebatan dalam Volksraad—semacam Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada harinya, Natsir mempresentasikan analisisnya di muka kelas. Ia menyodorkan bukti bahwa tidaklah benar Jawa menerima keuntungan dari pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang untung, kata dia, tetap saja kaum kapital dan pejabat bupati yang memaksa rakyat menyewakan tanahnya kepada pabrik dengan harga rendah.
Empat puluh menit menyampaikan analisisnya dengan bahasa Belanda yang rapi, seluruh kelas sunyi-senyap. Natsir melirik gurunya. Meneer itu diam. Natsir puas.
Hidup dalam didikan sekolah Belanda, Natsir melek terhadap dampak buruk penjajahan. Jiwa perlawanannya menyala-nyala. Ketertarikannya pada politik mulai bertumbuh. Apalagi, beberapa bulan sebelumnya, ia bertemu dengan A. Hassan, pria keturunan India asal Singapura yang kemudian menjadi ahli agama di organisasi Persatuan Islam. Kepada Hassanlah, Natsir datang menimba agama, menulis, dan berdiskusi.
Masa-masa itu Natsir juga memasuki Jong Islamiten Bond (JIB) cabang
Sebagai aktivis politik, Natsir juga rajin berinteraksi dengan tokoh pergerakan waktu itu. Ia pun mendengarkan pidato Soekarno. Juga pada rapat umum Partai Nasional Indonesia yang diselenggarakan 17 Oktober 1929 di gedung bioskop Oranje-Casino,
Namun Natsir tak sepaham dengan Soekarno soal cara memandang Islam. Ia memilih berjuang dengan caranya, menulis di majalah bulanan Pembela Islam yang tersebar ke seluruh
Amien Rais, yang bergaul lama dengan Natsir, mengatakan Natsir muda sesungguhnya seorang kutu buku. Ia melahap buku-buku filsafat Barat, baik kuno maupun modern. Ia membaca buku sejarah, sastra, dan rajin mengikuti berita internasional dari berbagai jurnal.
Natsir juga merajang habis karya-karya Snouck Hurgronje di perpustakaan, di antaranya Netherland en de Islam, buku yang memaparkan strategi Hurgronje dalam menghadapi Islam. Buku ini membuat Natsir bertekad melawan Belanda melalui pendidikan.
Jika sedang tak membaca atau sekolah, sesekali Natsir menonton bioskop. Kadang ia bervakansi ke Jaarbeurs—pasar malam yang digelar setahun sekali di
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi. 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
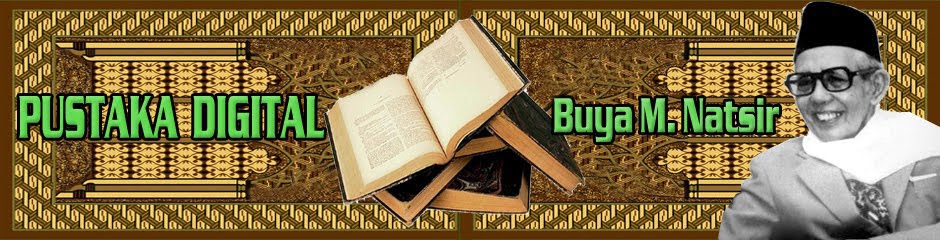
Tidak ada komentar:
Posting Komentar