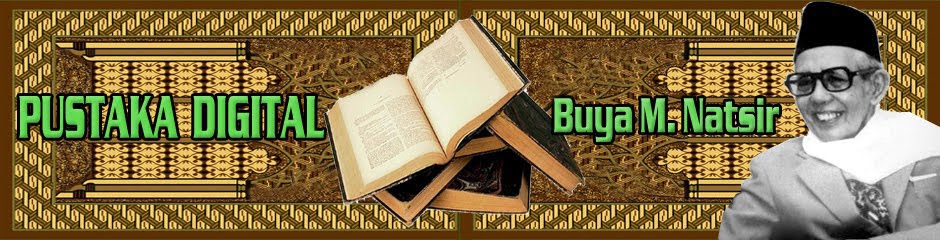Muqaddimah
Sebagai seorang pemimpin, yang juga seorang manusia biasa, tidak ma'shum, tentu tidak dapatluput dari berbagai kesalahan. Namun bukan berarti penulis tidak mau mengkritik, tetapi memang kepribadian Pak Natsir adalh susah untuk dikritik (dalam arti dicari kesalahan-kesalahannya) semasa beliau memimpin bangsa dan ummat ini, bahkan sampai akhir hayatnya. Sebagaimana yang lazim diketahui bahwasannya Allah Swt. telah mengisyaratkan di dalam al-Qur'an tentang kecintaan manusia terhadap berbagai jenis kesenangan:
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[1] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
Begitu pula dengan fitnah yang tidak jarang menyebabkan seorang pemimpin jatuh saat ia berada di puncak kepemimpinannya, yaitu harta, tahta dan wanita. Namun tidak demikian halnya dengan Pak Natsir. Tidak satupun dari ketiga hal tersebut mampu mempengaruhi apalagi menggelincirkannya.
Dari sisi harta, beliau tidak mampu mewariskan harta kepada keluarganya kecuali sedikit. Tidak sebanding jika disamakan dengan kekayaan pemimpin-peminpin saat ini yang dapat mewariskan kepada keluarga besarnya dalam jumlah yang sangat banyak bahkan melimpah. Begitu pula halnya dengan tahta, beliau adalah sosok yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai sebuah cita-cita apalagi ambisi. Pak Natsir menjadi Perdana Menteri, Menteri Penerangan, Sekjen Rabithah Alam Islami, Ketua Umum Masyumi ataupun ketua Dewan Da'wah Islamiyah Idonesia, bukanlah ia dapatkan dari hasil perebutan kursi/kedudukan tetapi itu semua semata-mata beliau raih adalah karena diberi amanah bukan mencari-cari amanah yang akhirnya justru khianat. Apalagi terbuai oleh wanita, sama sekali tidak.
Begitulah Pak Natsir. Oleh karenanya sangatlah menarik, tidak usang dan juga tidak habis-habisnya bila kita mengkaji tokoh ini.
B. Definisi dan Teori Kepemimpinan
Agar penulisan makalah ini sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu menngambarkan secara jelas bagaimana kepemimpinan Pak Natsir dalam Masyumi, maka perlu dijelaskan secara rinci pula akar kata dari istilah kepemimpinan tersebut.
Istilah kepemimpinan tidak dapat terlepas dari kata "memimpin" yang memiliki beberapa arti yaitu: memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun atau menunjukkan jalan, dsb); mengetuai atau mengepalai (dalam rapat atau perkumpulan, dsb); memandu; memenangkan paling banyak; melatih (mendidik, mengajari, dsb). Juga ada kata "terpimpin" yang berarti dapat dipimpin atau terkendali, serta ada pula kata "pemimpin" yang memiliki dua arti: orang yang memimpin dan petunjuk; buku petunjuk (pedoman).[2]
Para ahli ada yang menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses seseorang mempengaruhi orang lain untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Mereka yang memegang jabatan sebagai pemimpin menerapkan seluruh atribut kepemimpinannya (keyakinan, nilai-nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan ketrampilan). Jadi seorang pemimpin berbeda dari majikan, dan berbeda dari manajer. Seorang pemimpin menjadikan orang-orang ingin mencapai tujuan dan sasaran yang tinggi, sedangkan seorang majikan menyuruh orang-orang untuk menunaikan suatu tugas atau mencapai tujuan. Seorang pemimpin melakukan hal-hal yang benar, sedangkan seorang manajer melakukan hal-hal dengan benar (Leaders do right things, managers do everything right).[3]
Sedangkan arti "kepemimpinan" itu sendiri adalah mencakup: perihal pemimpin dan cara memimpin.[4] Siapa dan bagaimana karakter serta sikap dan tindakan sosok Pak Natsir, gaya atau etika dalam memimpin, menunjukkan serta membimbing masyarakat dan umat ataupun kelompok (partai Masyumi)-tanpa menafikan kepemimpinan beliau semasa hidupnya secara umum yang akan terlihat di dalam makalah kecil ini.
Dalam berbagai kajian kita dapat menjumpai beberapa teori dan istilah yang biasa disebut oleh para peneliti sebagai model kepemimpinan, yaitu:[5]
A. Tipe Laissez-faire; yaitu pemimpin yang tidak bisa menjalin hubungan baik dengan bawahan, dan juga tidak bisa berkomitmen dalam menyelesaikan tugas. Biasanya pemimpin semacam ini "mendelegasikan dan menghilang". Karena ia tidak berkomitmen untuk menyelesaikan tugas, maka ia mengijinkan anak buahnya melakukan apapun yang mereka kehendaki dan lebih suka menghindar dari proses pengambilan keputusan dalam tim dengan membiarkan timnya menyelesaikan pekerjaan itu sendiri.
B. Tipe Autocratic; yaitu pemimpin yang berikap otoriter terhadap bawahannya. Pemimpin semacam ini sangat ketat dalam mengatur jadwal kerja, tidak mengijinkan bawahannya mempertanyakan atau mendiskusikan tugas yang diberikan. Jika ada kesulitan, ia cenderung mencari siapa yang salah ketimbang mencari apa dan bagaimana kesalahan itu terjadi. Ia tidak mengenal toleransi, dan menganggap remeh setiap masukan dari bawahannya, sehingga bawahannya tidak mau memberikan sumbangan pemikiran atau pengembangan, karena selalu dianggap remeh.
C. Tipe Country-Club; yaitu pemimpin yang menggunakan upah untuk menegakkan disiplin dan untuk memotivasi tim dalam mencapai tujuan. Ia lebih mengutamakan hubungan dari pada hasil kerja. Ia kurang tegas dalam menegakkan disiplin karena takut merusak hubungan dalam tim.
D. Tipe Democratic/Tim; yaitu pemimpin yang memimpin dengan contoh positif. Ia melibatkan seluruh timnya untuk mengungkapkan potensi mereka seluas-luasnya. Ia memotivasi tim untuk mencapai sasaran seefektif mungkin, dan bekerja tanpa kenal lelah untuk menguatkan ikatan di antara anggota tim.
E. Tipe Manajer Organisasi; yaitu pemimpin yang memimpin dengan keseimbangan
Sejarah MASYUMI
Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7-8 November 1945 dan sekaligus berpusat di Jogjakarta sampai tanngal 1 Pebruari 1950. Kongres ini dihadiri oleh sekitar lima ratus utusan organisasi sosial keagamaan yang mewakili hampir semua organisasi Islam yang ada, dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Kongres memutuskan untuk medirikan majelis syuro pusat bagi umat Islam Indonesia yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam, yang secara resmi bernama Partai Politik Islam Indonesia “MASYUMI”. Dengan Kongres Umat Islam Indonesia ini, pembentukan Masyumi bukan merupakan keputusan beberapa tokoh saja, tapi merupakan keputusan “seluruh umat Islam Indonesia”.[6]
Segera setelah berdiri, Masyumi tersebar merata di segenap penjuru tanah air Indonesia bahkan hampir setiap kecamatan terdapat kepengurusan anak cabang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1950, secara resmi tercatat ada 237 Cabang (Tingkat Kabupaten), 1.080 Anak Cabang (tingkat Kecamatan) dan 4.982 Ranting (tingkat Desa) dengan jumlah anggota sekitar 10 juta orang.[7] Hal itu dapat terjadi karena dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang menjadi pendukung Masyumi. Ada 8 unsur organisasi pendukung Masyumi yakni NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Mai’iyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Dengan demikian Masyumi berhasil menyatukan organisasi dan umat Islam Indonesia dalam satu wadah perjuangan. Meski pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri.
Sejarah bangsa Indonesia mencatat nama besar Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai Islam terbesar yang pernah ada. Masyumi pada masanya sejajar dengan Partai Jama’atul Islam di Pakistan dan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Banyak yang lupa akan hal ini, dan memang dalam pendidikan politik nasional kebesaran Masyumi seolah tertutupi oleh arus besar lain, Nasionalisme dan Developmentalisme. Padahal dalam masa keberadaannya, Masyumi sangat identik dengan gerakan politik Islam yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks kenegaraan.[8]
Selain mempersatukan umat Islam Indonesia, alasan lain yang menjadi pertimbangan didirikannya Masyumi adalah agar Islam memiliki peranan yang signifikan ditengah arus perubahan dan persaingan di Indonesia saat itu. Tujuan didirikannya Masyumi, sebagaimana yang terdapat dalam anggaran Dasar Masyumi tahun 1945, memiliki dua tujuan. Pertama, menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia dan agama Islam. Kedua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.
Partai yang berdirinya diprakarsai oleh M. Natsir ini menyebutkan didalam Anggaran Dasarnya bahwa tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam didalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Ilahi. Kini, ia telah berusia 64 tahun.
Pokok Bahasan
Pak Natsir dan Kepentingan Rakyat
Dalam tindakannya Pak Natsir begitu sangat terlihat sebagai seorang pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat. Sebagai seorang ketua umum partai Masyumi, beliau memberikan arahan dan pandangannya bagi partai ini untuk dapat berkiprah di lapangan yang strategis, yaitu:[9]
- lapangan parlementer/perwakilan (legislatif)
- lapangan pemerintahan (eksekutif)
- lapangan pembinaan ummat
Sebuah gagasan yang begitu mulia. Jika dilihat kondisi saat ini, maka begitu sangat kontras dengan masa-masa awal kemerdekaan dulu. Sebagian calon-calon wakil rakyat, dengan sistem yang ada yaitu demokrasi (para calon wakil rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan dirinya dan memperebutkan kursi); sampai pada akhirnya harus mengalami stres, gila bahkan bunuh diri karena tidak sanggup menanggung kekalahannya.
Jangankan gagasan membina ummat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Natsir diatas, berebut untuk masuk di legislatif atau eksekutif pun didasari dengan ambisi kekuasaan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Pak Natsir dan Masyumi kala itu yang dipimpinnya, ia berjuang adalah lillah. Dalam pidatonya tanggal 7 November 1956 pada acara peringatan lahirnya Masyumi yang ke 11 Pak Natsir mengungkapkan:
Adapun yang mengenai lapangan pemerintahan, sebagaimana partai-partai politik yang lain, Masyumi juga berjuang untuk mendapat kedudukan dalam kabinet dan aparat pemerintahan lainnya. Perjuangan itu bukanlah untuk merebut kedudukan an sich (semata-mata), akan tetapi justru untuk turut melaksanakan dan mengambil tanggungjawab menjalankan eksekutif negara. Selain dengan duduknya dalam pemerintahan ia dapat melaksanakan cita-citanya didalam batas-batas seperti yang diterangkan tadi, maka salah satu pedoman yang penting yang senantiasa dipegang olehnya dalam tiap-tiap kesempatan turut memegang pemerintahan ialah mengusahakan kepentingan umum dan rakyat secara keseluruhan dengan tidak memandang tingkatan dan golongan. Semboyan yang dipakainya bukanlah ”kami berjuang untuk kami, tetapi kami berjuan untuk kita", untuk keseluruhan rakyat Indonesia.[10]
Pak Natsir juga mengingatkan terhadap nasihat Sjafruddin Prawiranegara yang ia sebut sebagai analisa "Indonesia Dipersimpangan Jalan".
Pak Syaf (sapaan Sjafruddin Prawiranegara) memperingatkan:
Apabila para pemimpin rakyat pada suatu saat tidak sanggup lagi bekerja betul-betul untuk kepentingan rakyatnya, apabila kedudukan atau kursi sudah menjadi tujuan dan bukan lagi menjadi alat maka yang akan mengancam negara kita ialah bahwa demokrasi akan tenngelam dalam koalisi dan kemudian koalisi akan dimakan oleh anarki dan anarki akan diatasi oleh golongan-golongan yang bersenjata itu.[11]
Masyumi dibawah kepemimpinan Pak Natsir telah jauh-jauh hari mengajukan ide agar daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia diberikan Otonomi Daerah. Hal ini diantaranya adalah agar kemauan rakyat benar-benar dapat terpenuhi.
Bagi Pak Natsir, negeri yang telah berhasil merdeka ini haruslah diisi dan dibangun. Diisi dengan pembangunan dan dasar-dasar keadilan sehingga dapat memberikan kebahagiaan penghidupan untuk seluruh rakyat. Tidak menimbulkan perasaan-perasaan tidak puas bagi daerah-daerah tertentu karena kebutuhan mereka kurang terpenuhi, padahal mereka mampu menghasilkan sumber penghasilan negara yang cukup tinggi.[12]
Menurut Pak Natsir dengan partainya, bahwa perasaan-perasaan kurang puas itu akan dapat disalurkan apabila daerah-daerah diberikan hak-hak yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam bentuk otonomi yang luas. Dan diberi alat-alat yang cuku dan dijamin oleh undang-undang. Dalam hubungan inilah partai sejak dahulu selalu mendesak agar segera dibuat UU Perimbangan Keuangan (financieele verhouding) antara Pusat dan Daerah. Masyumi pada pokoknya dapat menyetujui supaya ditetapkan jumlah prosentase tertentu dar hasil-hasil utama yang terdapat di daerah masing-masing, sehingga daerah tidak hanya menggantungkan nasibnya kepada belas kasihan dan dari uang kerahiman Pemerintah Pusat saja. Apabila UU tersebut sudah terealisasikan maka Masyumi yakin bahwa perasaan tidak puas dari daerah-daerah dapat segera diredakan, karena ini adalah persoalan yang sangat mendesak.[13]
Mr. Mohammad Roem (biasa disapa Pak Rum), pernah memberikan cerita ringan sarat makna tentang kepedulian dan kedekatan Pak Natsir dengan masyarakat. Kata pak rum, ketika Pak Natsir masih hidup rumahnya selalu dipenuhi tamu. Sehingga pak Rum pernah ditanya oleh banyak orang, Pak Natsir itu dokter apa, kok pasiennya banyak sekali? Dengan ringan pula Pak rum menjawab bahwa Pak Natsir itu dokter yang bisa menyembuhkan jiwa orang. Bahkan kata KH. Hasan Basri, jika ada pasien yang meminta uang, Pak Natsir selalu memberinya.[14]
Demikian pula kesederhanaan Pak Natsir yang tidak mungkin dapat disembunyikan. Beliau adalah pemimpin dan negarawan kaliber dunia, tetapi sepeninggalnya tidak mewariskan harta dan kekeyaan yang cukup berarti. Tetapi justru beliau meninggalkan kekayaan rohaniyah dan sumber ilmu dan teladan yang begitu banyak. Berjilid-jilid tulisan telah beliau tinggalkan untuk dapat dipelajari, dikritisi dan diteladani oleh generasi-generasi dibelakangnya yang masih memiliki semangat juang untuk tegaknya ajaran Islam dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang ia cita-citakan.
Patriotisme dan nasionalisme Pak Natsir perlu dihayati lebih baik lagi. Bukan hanya andil Pak Natsir sangat besar, jika bukan yang terbesar-untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mosi integralnya yang sangat terkenal, tapi juga wawasan nasionalismenya terbukti sangat jernih dan mendalam. Puluhan tahun yang lalu bliau telah mewanti-wanti bahwa nasionalisme yang baik adalah patriotisme yang tidak jatuh dalam xenophobisme.solipsis atau menganggap bangsa sendiri paling baik dan benar. Nasionalisme Pak Natsir adalah dalam kontek universalisme dan ini benar-benar terbukti di era globalisasi sekarang ini.[15] Artinya tidak picik, eksklusif dan
Tidak Sengaja Jadi Politikus
Dalam sebuah dialog ringan antara seorang wartawan muda dari media harian Berita Buana[16][17] dengan M. Natsir terlihat betapa beliau tidaklah menjadikan profesi politik sebagai tujuan hidupnya. Ketika Pak Natsir dikritik oleh sang wartawan bahwasannya beliau tidaklah tepat menjadi seorang politikus, tetapi lebih tepat sebagai seorang pendidiki, filosof atau pemikir yang tidak terjun langsung di kancah politik praktis. Menjawab kritikan tersebut beliau mengatakan: "Memang saya jadi politikus tidak sengaja, secara tersambil".
Pak Natsir adalah a smiling politician- seorang politikus yang penuh senyum. Kepada kawan maupun lawan politiknya ia selalu bersikap ramah, mengedepankan akhlak Islam, sehingga tidak ada bagi dirinya istilah machiavelisme.
Pak Natsir dengan Masyumi
Setelah Masyumi membubarkan diri karena tekanan rezim Soekarno pada tahun 1960[18], maka pada tanggal 26 Februari 1967, atas undangan pengurus masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, para alim ulama dan zu'ama berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang berhubungan dengan usaha pembangunan umat, juga tentang usaha mempertahankan aqidah di dalam kesimpangsiuran kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Musyawarah menyimpulkan dua hal sebagai berikut[19]:
- Menyatakan rasa syukur atas hasil dan kemajuan yang telah dicapai hingga kini dalam usaha-usaha dakwah yang secara terus menerus dilakukan oleh berbagai kalangan umat, yakni para alim ulama dan para muballigh secara pribadi, serta atas usaha-usaha yang telah dicapai dalam rangka organisasi dakwah.
- Memandang perlu (urgent) lebih ditingkatkan hasil dakwah hingga taraf yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu keselarasan antara banyaknya tenaga lahir yang dikerahkan dan banyaknya tenaga batin yang dicurahkan dalam rangka dakwah tersebut.
Untuk menindaklanjuti kesimpulan pada butir kedua di atas, musyawarah para ulama dan zu'ama mengkonstatir terdapatnya berbagai persoalan, antara lain:
- Mutu dakwah yang di dalamnya tercakup persoalan penyempurnaan sistem perlengkapan, peralatan, peningkatan teknik komunikasi, lebih-lebih lagi sangat dirasakan perlunya dalam usaha menghadapi tantangan (konfrontasi) dari bermacam-macam usaha yang sekarang giat dilancarkan oleh penganut agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan (antara lain faham anti Tuhan yang masih merayap di bawah tanah), Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan sebagainya terhadap masyarakat Islam.
- Planning dan integrasi yang di dalamnya tercakup persoalan-persoalan yang diawali oleh penelitian (research) dan disusul oleh pengintegrasian segala unsur dan badan-badan dakwah yang telah ada dalam masyarakat ke dalam suatu kerja sama yang baik dan berencana.
Dalam menampung masalah-masalah tersebut, yang mengandung cakupan yang cukup luas dan sifat yang cukup kompleks, maka musyawarah alim ulama itu memandang perlu membentuk suatu wadah yang kemudian dijelmakan dalam sebuah Yayasan yang diberi nama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat Dewan Dakwah. Pengurus Pusat yayasan ini berkedudukan di ibu kota negara, dan dimungkinkan memiliki Perwakilan di tiap-tiap ibukota Daerah Tingkat I serta Pembantu Perwakilan di tiaptiap ibukota Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Pak Natsir mengatakan:
"Politik dan dakwah itu tidak terpisah. Kalau kita berdakwah, membaca al-Qur'an dan hadits, itu semuanya politik. Jadi kalau dulu kita berdakwah lewat jalur politik dan sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah. Ya mengaji politik begitulah. Saya merasa bahwa DDII itu tidak lebih rendah daripada politik. Politik tanpa dakwah itu hancur. Lebih dari itu, bagi saya untuk diam itu tidak bias".[20]
Penutup
Setelah kita membaca kiprah dan tauladan Pak Natsir diatas maka terlihat bahwa sebagai pemimpin bangsa, pahlawan nasional dan negarawan panutan ini selalu mengedepankan kepentingan ummat dan bangsa dalam sikap dan tindakannya. Juga dapat dipetik pelajaran bahwa perilakunya baik dia sebagai politisi maupun sebagai da'i, sesungguhnya dia mencerminkan dirinya sebagai seorang pendidik. Atau sebaliknya bahwa perannanya sebagai politisi maupun sebagai seorang pendidik, sesunggunhnya dia mencerminkan dirinya sebagai seorang da'i, yang berarti mampu memberikan nasehat dan pelajaran baik dengan lisannya, tangannya ataupun sikap serta tindakannya sehingga beliau dirasakan oleh ummat dan bangsa sebagai sosok panutan. Pendidik dan da'i adalah bagaikan dua sisi mata uang yang juga tidak dapat dipisahkan dari sosok Pak Natsir, sebagaimana tidak dapat dipisahkannya antara politik dan da'wah yang melekat pada diri beliau.
Satu hal lagi yang harus ditegaskan dalam kesimpulan ini bahwa jika digunakan teori-teori kepemimpinan sebagimana telah disebutkan dimuka, maka Pak Natsir bukanlah tipe pemimpin yang Laissez-faire; yang tidak bisa menjalin hubungan baik dengan bawahan, juga bukan pemimpin yang Autocratic; yang berikap otoriter terhadap bawahannya, apatah lagi memimpin dengan upah untuk menegakkan disiplin, tidaklah demikian.
Pak Natsir adalah tokoh yang mampu memimpin dengan gaya Democratic/Tim; yaitu memimpin dengan contoh positif. Ia melibatkan seluruh timnya untuk mengungkapkan potensi mereka seluas-luasnya. Ia memotivasi tim untuk mencapai sasaran seefektif mungkin, dan bekerja tanpa kenal lelah untuk menguatkan ikatan di antara anggota tim. Begitu pula beliau adalah sebagi Manajer Organisasi yang memimpin dengan keseimbangan. Beliau mampu membuktikan diri sebagai Qudwah Hasanah bagi yang dipimpinnya yaitu dari lingkup yang paling kecil; keluarga, organisai, umat Islam dan rakyat Indonesia bahkan dunia Islam pada umumnya. Tentu dengan kadar kemampuannya sebagai manusia biasa, bukan Nabi....Semoga Bermanfaat
Sumber : Ditulis oleh Ujang Habibi (STID Mohammad Natsir)
http://www.stidnatsir.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:kepemimpinan-politik-m-natsir-studi-kasus-dalam-masyumi&catid=29:artikel-dosen&Itemid=86
Referensi
- Berita Buana, Selasa 9 Februari 1993
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. 10, tahun 1999, hlm. 769
- Kementrian Penerangan RI, Kepartaian Di Indonesia, tt.
- Lukman Hakim (penyunting), Pemimpin Pulang: Rekaman Peristiwa Wafatnya M. Natsir, Jakarta: Yayasan Piranti Ilmu, cet. 1, 1993
- M. Natsir, Capita Selecta 3, Jakarta: PT Abadi kerjasama dengan Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir pemikiran dan Perjuanganya serta Yayasan Capita Selecta, cet. 1, th. 2008
- M. Natsir, Politik Melalui Jalur Dakwah, Jakarta: PT. Abadi, cet. 2, tahun 1998
- Majalah SAKSI, edisi bulan Oktober 2005
- Panitia Buku Peringatan M. Natsir/M. Roem 70 Tahun, Mohammad Pak Natsir; 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, Jakarta: Pustaka Antara, cet. 1, th. 1978
- blogspot.com, dikutip tgl 1 Mei 2009 pukul 11.03
- groups.yahoo.com, 26 mei 09: 17.02
- petrusfs.blogspot.com
- www.republika.co.id 26 mei 09/ 16.59