Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.
Pada 1978, saat Mohammad Natsir berumur 70 tahun, Mohammad Roem mengkhawatirkan kesehatan karibnya itu. ”Andainya ia mau mengurangi tamunya, tentu kesehatannya akan lebih baik,” tulis Roem, kawan seperjuangan Natsir, dalam buku Mohammad Natsir, 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan (Pustaka Antara, 1970). Jika Natsir sakit—kata Roem mengutip keterangan Nurnahar, istri Natsir—pasti karena terlalu banyak menerima tamu. Meski kerap berbaring dan tak kuat bangun karena kehabisan tenaga melayani tamu, Natsir tak pernah menolak orang yang datang.
Natsir, kata Roem, punya satu sifat langka yang dirindu orang. Jika ada orang bercerita—entah berupa pendapat entah kisah sedih—Natsir bisa mendengarkannya dengan penuh perhatian. Seolah ia ikut merasakannya. Orang kerap merasa lega bercerita kepadanya, meski soal yang diceritakan itu tak ada jalan keluarnya. Begitu pula jika Natsir bercerita atau berpendapat, ia akan mengisahkannya dengan segala perasaan dan emosi yang ada. ”Kawan-kawan menjadi meyakini apa yang Natsir ceritakan. Mereka bersedia membantu Natsir dan mengikutinya,” tulis Roem dalam tulisan ”Kelemahan atau Kebesaran Natsir”.
Sikap penuh pengertian dan mau mendengar pendapat orang berasal dari endapan pengalaman hidup Natsir. Pria asal Alahan Panjang, Sumatera Barat, tersebut menempuh jalan yang sukar dalam hidupnya sebagai anak penghulu kecil. Barangkali juga dilatari wataknya sebagai guru. Selain itu, seperti kerap diceritakan Natsir kepada kawan-kawannya, semua itu adalah buah perjumpaan yang mengesankan dengan guru-guru batinnya.
Natsir bercerita pernah dibikin terharu oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam. Natsir bertemu dengan pria gagah berkumis lebat itu di Stasiun
Kisah lainnya adalah perkawanannya dengan A. Hassan, seorang ustad yang dikenalnya semasa bersekolah dan mengambil diploma guru di
”Teruskan kerja Tuan dulu. Jangan terganggu oleh saya. Tidak ada yang penting-penting,” kata Natsir berdalih tak enak mengganggu kerja A. Hassan. Tapi A. Hassan selalu ”melayani” Natsir, seolah percakapannya dengan pemuda tanggung itu lebih penting ketimbang bekerja. Natsir pun mengakui percakapan dan tukar pikiran yang dilakukannya dengan A. Hassan sangat mempengaruhi jiwa dan arah hidupnya kelak.
Cara Natsir memandang kekuasaan pun sangat bersahaja. Pegawai Kota Praja Bandung ini (saat penjajahan Jepang) mengaku ”dijerumuskan” Kahar Muzakkar, seorang kawan dekatnya, ke pentas pergolakan nasional.
Ceritanya amat sepele. Menjelang proklamasi, Natsir datang dan menginap di rumah Kahar Muzakkar di Jalan Teuku Umar,
Penjaga pintu gedung yang mencatat nama-nama orang yang hadir ternyata salah dengar. Ia menulis nama Mohammad Natsir dalam daftar anggota KNI. Maka jadilah Natsir anggota KNI, yang diterimanya tanpa keberatan. Kelak, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan
Dengan segala tempaan di masa lalunya itulah Natsir berhasil menjadi ketua terlama Partai Masyumi (1949-1958). Partai Islam ini juga berhasil diantarkannya memenangi posisi kedua dalam pemilihan umum 1955. Sebagai orang yang tak pernah mengenyam bangku perguruan tinggi, prestasi Natsir sungguh luar biasa. Apalagi, seperti diungkapkan Yusril Ihza Mahendra—salah satu anak didik Natsir—partai berlambang bulan bintang itu penuh orang yang berbeda aliran dan karakter politik.
Masyumi saat itu adalah biduk yang memuat orang Islam dari banyak kalangan: ada abangan, sarjana didikan Belanda, sampai santri Nahdlatul Ulama. ”Selain intensitas dalam pandangan-pandangan ideologi. Juga ada faktor etnis,” kata Bachtiar Effendi, peneliti Masyumi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Menurut Yusril, elite Masyumi berasal dari alumni Jong Islaminten Bond dan Islamic Studie Club. Sebagian mereka juga pernah mendirikan Partij Sarekat Islam
Tokoh macam Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, Abu Hanifah atau Mahmud Latjuba (kakek Sofia Latjuba) lebih banyak memakai istilah-istilah Belanda ketimbang Arab. Dalam soal
Di awal merdeka memang terlihat Natsir memilih mendahulukan kepentingan negara ketimbang partai atau dirinya sendiri. Ketika pemerintah Republik
Mohammad Chudori, 83 tahun, mantan wartawan Antara, yang saat itu menjadi anggota Laskar Hizbullah, menjadi saksi sulitnya posisi Natsir. Pada 1949, karena merasa terancam lantaran ajakan baiat Kartosoewirjo sebagai Tentara Islam
Namun sejarah mencatat, Natsir akhirnya memilih berhadapan dengan Kartosoewirjo, yang juga pendiri Masyumi tersebut. ”Partai Masyumi hendak mencapai maksudnya dengan jalan demokratis parlementer, melalui jalan sesuai Undang-Undang Dasar… dan tidak dengan jalan kekerasan,” tulis Natsir—saat itu sudah menjadi perdana menteri—dalam Pengumuman Sikap Dewan Pimpinan Masyumi atas Pemberontakan Darul Islam, Januari 1951. Natsir sendiri pernah melobi Kartosoewirjo agar menyerah melalui bantuan A. Hassan. Sayang, tidak berhasil. Kartosoewirjo pun akhirnya tertangkap 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada Agustus tahun itu juga.
Di usia tuanya, ketika memimpin Dewan Dakwah Islamiyah, Natsir makin dicintai. Suatu hari pada 1984, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais (saat itu aktivis Muhammadiyah) menumpang mengetik di DDI untuk menyiapkan bahan seminar di
Natsir memang telah membuktikan mampu berkawan dengan siapa saja.
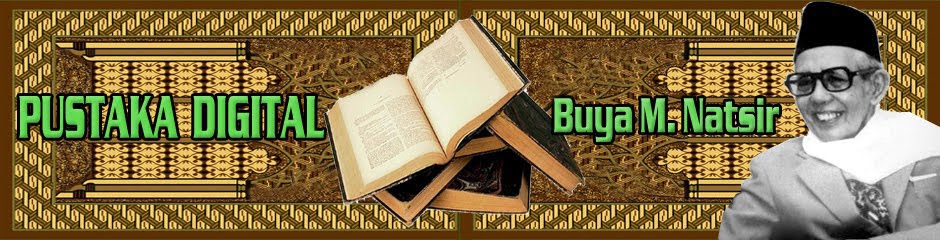
Tidak ada komentar:
Posting Komentar