Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.
Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis
Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubungan dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.
Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di
Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.
Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak 1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.
Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam, Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.
Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat pada
Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana menteri. Natsir memberikan wejangan tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin harus seperti tukang kayu yang terampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.
Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir (1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum.
Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu. Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.
Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah untuk Prawoto di Yogyakarta.
Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei aktif di Partai
Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita
Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967. Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita,
”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan
Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.
”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama nyemplung di Petisi 50.
Suatu ketika, tidak sengaja Chris bertemu Natsir di kantor Lembaga Bantuan Hukum
Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.
Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya, ”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”
Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir membubarkan kabinetnya yang baru berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi, majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
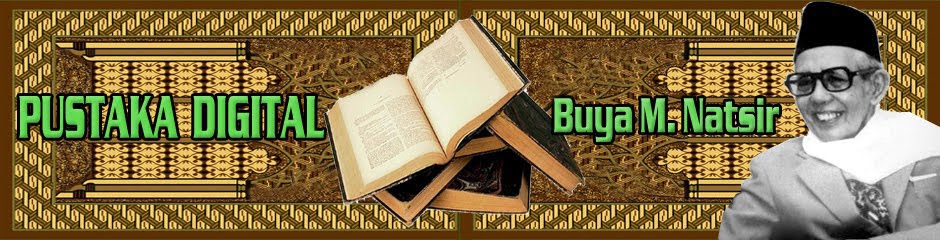
Tidak ada komentar:
Posting Komentar