Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.
SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah tahanan di daerah
Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.
Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.
Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan
Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke
Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke
Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke
Menurut Deliar Noer, peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.
Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Ternyata itu janji kosong belaka.
Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.
Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar,
Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin
Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini,
Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan
Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi
Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Syachroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke
Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto. ”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di
Ia mengirim
Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah berhasil. Pemerintah
Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan rezim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar negeri.
Larangan itu terus dikenakan kepada Natsir pada 1990, ketika Universiti Kebangsaan
Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri
Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupakan sang tokoh di akhir hayatnya.
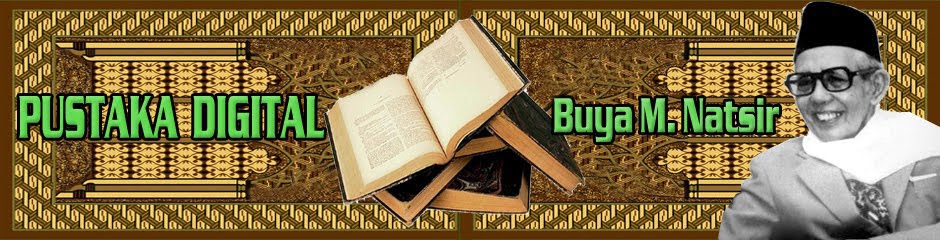
Tidak ada komentar:
Posting Komentar